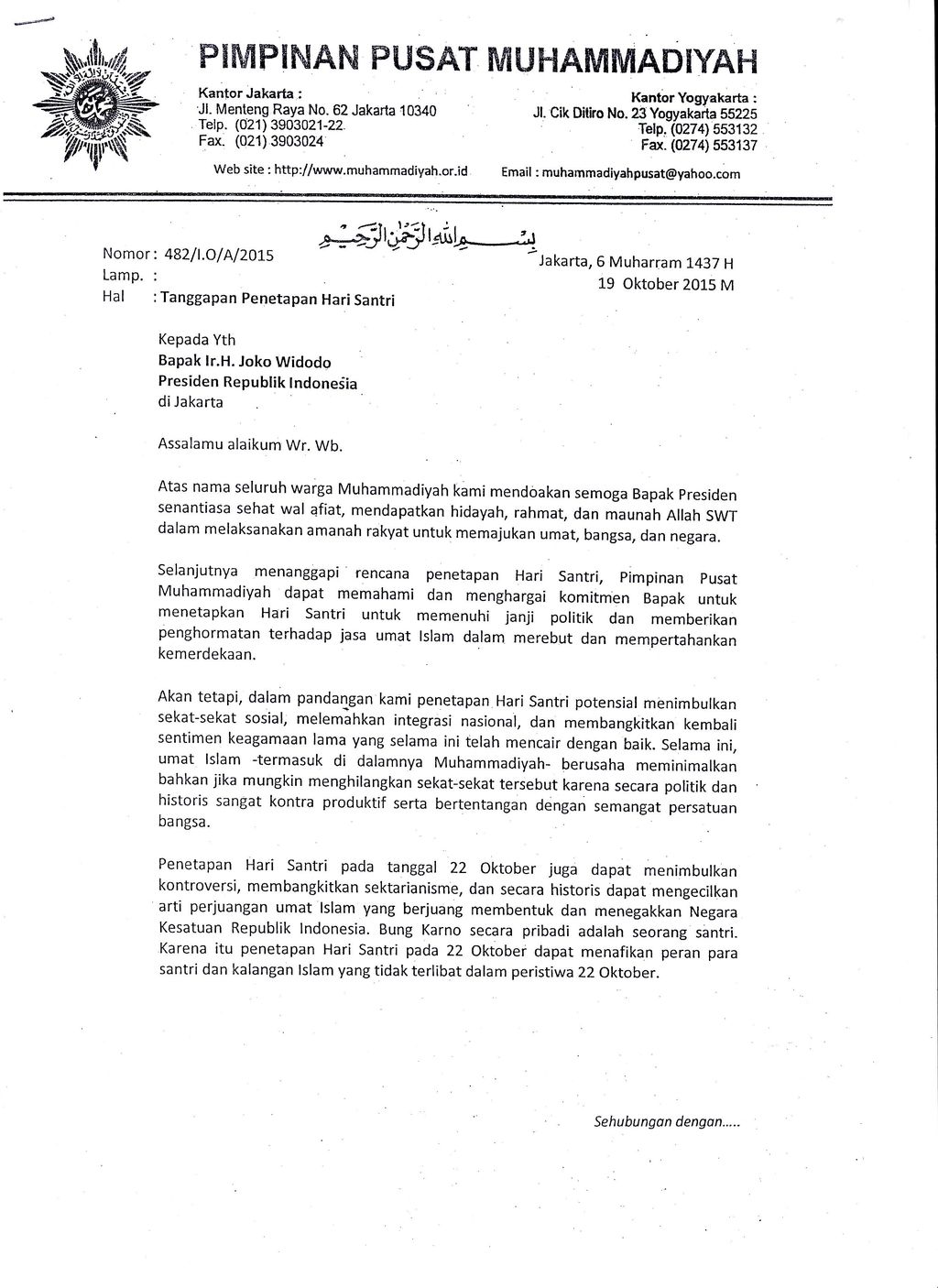Dalam Islam, di antara tujuan pernikahan
adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Sebagaimana
firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:
وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
“Dan di antara tanda-tanda
kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu
sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah)
bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Rum:21)
Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan
bahwa makna sakinah ada tiga: lita’tafu (saling mengikat hati), tamilu
‘ilaiha (condong kepadanya) dan tadma’inu biha (merasa tenang
dengannya). Seringkali sakinah disederhanakan dengan makna ketenangan.
Salah satunya, tenang karena syahwat telah tersalurkan secara halal. Dan
ketenangan itu tak bisa dicapai kecuali melalui pernikahan.
Dalam rangka mencapai ketenangan seperti
ini, suami istri perlu sama-sama terpuaskan. Dan memang suami istri
sama-sama memiliki hak yang sama untuk mendapatkannya.
Sebagaimana kaidah umum hak dan kewajiban berumah tangga sebagaimana firmanNya:
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
“Istri memiliki hak (yang harus
dipenuhi suami) sebagaimana kewajiban yang harus ia penuhi untuk
suaminya, dengan baik (dalam batas wajar).” (Q.S. Al Baqarah: 228)
Jadi dalam berhubunganpun, suami istri
harus menjadikan asas ini sebagai pedoman. Saling memenuhi hak pasangan,
saling bekerja sama dan saling menolong. Suami tidak boleh egois,
asalkan ia puas, lalu tidak peduli dengan pasangannya.
Suami yang tidak memenuhi hak istrinya
dalam hal kepuasan ini, meskipun karena ibadah, ia tidak diperbolehkan.
Sebab istrinya memiliki hak atasnya. Sebagaimana yang pernah dialami
oleh Abu Darda’ radhiyallahu ‘anhu.
آخَى النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم –
بَيْنَ سَلْمَانَ ، وَأَبِى الدَّرْدَاءِ ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا
الدَّرْدَاءِ ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً . فَقَالَ لَهَا
مَا شَأْنُكِ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِى
الدُّنْيَا . فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا .
فَقَالَ كُلْ . قَالَ فَإِنِّى صَائِمٌ . قَالَ مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى
تَأْكُلَ . قَالَ فَأَكَلَ . فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو
الدَّرْدَاءِ يَقُومُ . قَالَ نَمْ . فَنَامَ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ .
فَقَالَ نَمْ . فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ
الآنَ . فَصَلَّيَا ، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ
حَقًّا ، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ،
فَأَعْطِ كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ . فَأَتَى النَّبِىَّ – صلى الله عليه
وسلم – فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ النَّبِىُّ – صلى الله عليه وسلم
–صَدَقَ سَلْمَانُ
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah
mempersaudarakan Salman dan Abu Darda’. Suatu hari Salman mengunjungi
Abu Darda’. Ketika itu Salman melihat istri Abu Darda’ yakni Ummu Darda’
dalam kondisi kurang baik. Salman pun bertanya kepada Ummu Darda,
“Kenapa keadaanmu seperti ini?” Ia menjawab, “Saudaramu, Abu Darda’,
seakan-akan tidak lagi mempedulikan dunia.” Abu Darda’ kemudian datang.
Salman pun membuatkan makanan untuk Abu Darda’. Salman berkata,
“Makanlah”. Abu Darda’ menjawab, “Maaf, saya sedang puasa.” Salman pun
berkata, “Aku pun tidak akan makan sampai engkau makan.” Lantas Abu
Darda’ memakan makanan tersebut.
Ketika malam hari tiba, Abu Darda’ pergi
melaksanakan shalat malam. Melihat itu, Salman mengatakan, “Tidurlah”.
Abu Darda’ pun tidur. Namun kemudian ia pergi lagi untuk shalat.
Kemudian Salman berkata lagi, “Tidurlah”. Ketika sudah sampai akhir
malam, Salman berkata, “Mari kita berdua shalat.” Lantas Salman berkata
lagi pada Abu Darda’, “Sesungguhnya engkau memiliki kewajiban kepada
Rabbmu. Engkau juga memiliki kewajiban terhadap dirimu sendiri dan
engkau pun punya kewajiban pada keluargamu (melayani istri). Maka
tunaikanlah kewajiban-kewajiban itu secara proporsional.” Abu Darda’
lantas mengadukan Salman pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,
lantas beliau bersabda, “Salman itu benar” (HR. Bukhari)
Dalam riwayat yang lain disebutkan lebih teknis.
“Jika seseorang di antara kamu
berhubungan dengan istrinya, hendaklah ia lakukan dengan penuh
kesungguhan. Jika ia menyelesaikan kebutuhannya sebelum istrinya
mendapatkan kepuasan, maka janganlah ia buru-buru mencabut hingga
istrinya mendapatkan kepuasannya juga.” (HR. Abdur Razaq dan Abu Ya’la, dari Anas)
Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Ibnu
Taimiyah berpendapat, suami wajib menggauli istrinya sesuai dengan
kemampuan suami dan kecukupan istri.
Sedangkan Ibnul Qayyim Al Jauziyah
mengutip pendapat para gurunya yang menguatkan pendapat bahwa suami
harus memuaskan istrinya ketika berhubungan, jika memungkinkan,
sebagaimana dia wajib memuaskannya dalam memberi makan.
Adapun jika suami sakit atau secara
medis terhalang dari kemampuan memenuhi hal itu, maka penyelesaiannya
dikembalikan kepada keridhaan masing-masing. Sebab pada dasarnya,
pernikahan adalah ikatan yang dibentuk atas dasar keridhaan. Pun ketika
ada masalah dalam rumah tangga, hendaknya saling ridha menjadi
solusinya. Wallahu a’lam bish shawab.